Pejuang Lingkungan Terancam Proyek Energi Ramah Lingkungan
Penulis : Aryo Bhawono
Hukum
Rabu, 19 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Proyek energi hijau di Wawonii, Sulawesi Tenggara, dan Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, justru berbuah kriminalisasi. Riset menunjukkan label hijau proyek-proyek itu masih abal-abal.
Beatrix Dahelen masih ingat petuah orang-orang tua di desa tempatnya tinggal, Poco Leok, ketika ia dan anak-anak muda di kampung itu meminta nasihat perihal penolakan proyek geotermal. Jawaban mereka singkat, penolakan itu bukan kepentingan para tetua tapi anak-anak muda seperti dirinya.
“Penjelasan mereka adalah jika geotermal itu terus berlanjut yang rusak adalah masa depan kami. Kami akan kehilangan ladang, rumah, dan terusir karena tanah tak lagi menghidupi. Mereka bilang tinggal menunggu waktu untuk uzur kemudian meninggal, tapi hidup kami lah yang terus berlanjut dan menanggung dampaknya,” ucap dia dalam Workshop Nasional bertajuk “Para Penjaga Di Bawah Tekanan: Pembela Lingkungan dan Ruang Sipil di Indonesia Dalam Konteks Mitigasi Perubahan Iklim” di Jakarta pada Senin (18/11/2025).
Poco Leok adalah ironi proyek energi berlabel hijau. Protes demi ruang hidup oleh masyarakat atas proyek itu selalu berujung intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi, termasuk bagi kaum muda seperti dirinya.

Proyek itu merupakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5–6. Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit menetapkan Poco Leok sebagai lokasi proyek geothermal berkapasitas 2×20 MW melalui SK Bupati Manggarai No 188/500/10.16/IX/2024.
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 juga menempatkan pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 menjadi bagian program percepatan energi baru terbarukan.
Masyarakat menolak karena PLTP ini mengancam tanah leluhur serta sistem nilai sosial dan spiritual yang telah diwariskan secara turun- temurun.
Mereka juga khawatir kawasan hutan yang menjadi sumber air utama bagi beberapa desa di sekitarnya. Aktivitas pengeboran geothermal rawan menimbulkan longsor, pencemaran air panas, dan penurunan debit mata air.
 Masyarakat adat Poco Leok yang menolak wilayah adatnya dirampas untuk pembangunan PLTP Ulumbu, bentr
Masyarakat adat Poco Leok yang menolak wilayah adatnya dirampas untuk pembangunan PLTP Ulumbu, bentr
Beatrix merupakan salah satu interlokutor, (pemberi informasi) dalam riset “Para Penjaga di Bawah Tekanan: Pembela Lingkungan dan Ruang Sipil di Asia Tenggara Dalam Konteks Mitigasi Perubahan Iklim” yang dilakukan oleh Auriga Nusantara dan Dala Institute.
Sejak 2022, warga menggelar aksi ‘jaga kampung’ untuk menghalau survei geotermal yang memaksa dan bersiasat masuk ke Poco Leok. Hampir seluruh aksi jaga kampung itu juga diwarnai bentrok apalagi ketika polisi turut melakukan pengawalan. Pukulan, desakan, dan tendangan diterima warga.
Puncak kekerasan terjadi pada Oktober 2024 lalu, saat proses identifikasi Acces Road Wellpad D, Wellpad I, dan Acces Road Wellpad I. Aparat melakukan intimidasi dan penyerangan. Akibatnya puluhan orang luka-luka, sebagian di antaranya hingga tidak sadarkan diri.
Tiga warga sempat ditangkap dan mengalami tindak kekerasan. Bahkan seorang jurnalis Floresa, Herry Kabut, mengalami ditangkap, mengalami tindak kekerasan berupa penyekapan, pemukulan, dan perampasan alat-alat jurnalistik, termasuk foto.
Selain itu pada kejadian sebelumnya tujuh warga telah mendapat panggilan polisi atas penyelidikan dugaan tindak pidana ‘yang dengan sengaja menghalangi kegiatan pengusahaan pembangunan panas bumi dan/atau melakukan kekerasan terhadap pejabat’ yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan atau pasal 212 KUHP.
Warna kekerasan sama juga terjadi di Wawonii, Sulawesi Tenggara. Pulau kecil seluas 867 kilometer persegi itu menjadi bagian dari ambisi pemerintah untuk menjadi pemasok utama bahan baku kendaraan listrik melalui tambang nikel.
Warga menolak pertambangan ini karena memiliki kesadaran ekologis dan pengalaman panjang sebagai masyarakat pulau kecil. Tambang nikel mengancam lahan pertanian dan sumber air, tetapi juga pesisir yang menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga.
Interlokutor riset dari Wawonii, Wilman, menyebutkan konsesi nikel PT Gema Kreasi Perdana, anak perusahaan Harita Group, mulai hadir tahun 2008. Mereka mengantongi berbagai izin hingga mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Pada 2016, sosialisasi yang dilakukan perusahaan mendapat penolakan masyarakat. Namun bukannya melakukan koreksi, mereka justru membangun terminal khusus pada 2019. Pembangunan ini pun menutupi gugusan karang, tempat kawasan tangkap nelayan.
 Dari ketinggian tampak kondisi Pulau Wawonii akibat pertambangan nikel. Foto: Jatam Nasional.
Dari ketinggian tampak kondisi Pulau Wawonii akibat pertambangan nikel. Foto: Jatam Nasional.
Protes yang dilakukan warga pun menemui balasan yang sama dengan Poco Leok.
“Kemudian mereka melakukan kriminalisasi terhadap warga itu kurang lebih kami catat di tahun 2019 itu ada 27 warga dilaporkan dengan berbagai macam tuduhan," ucap Wilman.
Pasal yang dikenakan kepada warga beragam, mulai dari perampasan kemerdekaan orang lain, menduduki kawasan hutan, penghasutan dan penyebaran berita bohong, serta menghalang-halangi aktivitas perusahaan.
Tiga orang dari 27 warga yang ditangkap paksa, kata dia, sempat ditahan selama 40 hari. Hingga kini status hukum mereka tidak jelas.
Sementara kerusakan oleh operasi tambang terus terjadi. Sejak tahun 2022 tiga sumber mata air warga tercemari lumpur karena aktivitas itu.
"Kemudian ada sungai, Sungai Kiumolou itu sudah berwarna lumpur, warna kecoklatan. Kemudian ada Sungai Roko-Roko. Sungai Roko-Roko ini tempat di saat eh musim kesulitan ikan, kalau di sana dibilang musim timur itu kan kencang ombak. Jadi ikan itu eh kita juga kesulitan. Tetapi sungai ini menyediakan ikan namanya Lompa Mea," kata dia.
Direktur Hukum Auriga Nusantara, Roni Saputra, menyebutkan penelitian ini berfokus pada dampak mitigasi perubahan iklim terhadap masyarakat. Temuan di Poco Leok dan Wawonii menunjukkan adanya eksploitasi hijau (green capitalism) dalam praktik dengan tajuk mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah dan korporasi besar.
Para peneliti menangkap beberapa isu utama, pertama transisi energi yang dilakukan pemerintah melalui pendekatan Proyek Strategis Nasional (PSN) justru merupakan kebijakan top down yang bersifat otoritarian. Pendekatan ini justru menciptakan kerusakan dari struktur masyarakat sendiri.
Kedua, terjadi pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Penerapan FPIC merupakan hal utama pada setiap proses pembangunan energi. Sayangnya proses konsultasi sering tidak memenuhi standar etik itu sendiri dan mengabaikan persetujuan dari masyarakat lokal.
Ketiga, itu terjadinya pelanggaran eh keadilan energi. Masyarakat justru tidak mendapat distribusi manfaat yang adil akibat prosedur yang tidak transparan dan tidak inklusif serta kurangnya pengakuan terhadap budaya dan identitas masyarakat terdampak."
Keempat, transisi energi kemudian menimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan yang cukup luar biasa berupa konflik sosial, kriminalisasi warga, kekerasan, dan kerusakan lingkungan.
"Nah, dua hal ini diwakili Poco Leok dengan geotermal dan Wawonii dengan tambang nikel. Proyek energi terbarukan yang beroperasi di Indonesia itu dilakukan dalam kerangka kapitalisme hijau atau green capitalism,” ucap dia.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Jaelani, mengungkapkan temuan ini menjadi kontradiksi proyek energi hijau pemerintah. Ia sendiri merupakan legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tak menafikkan temuan ini.
“Saya juga pernah ke sana (Wawonii), dan mendapatkan keluhan sama,” ucapnya.
Daerah konstituennya dibanjiri izin pertambangan dan kawasan industri pengolahan nikel. Tambang akan meninggalkan bukaan hutan yang luar biasa hingga duka mendalam konflik sosial di masyarakat.
“Luka-luka bukan hanya tanah yang luka, masyarakat, batin, suasana kebatinan kita juga sudah tidak baik-baik saja."
Saat ini beberapa pejabat pemerintah daerah yang ditemuinya memberikan keluhan sama, semua perizinan dan investasi hanya dikelola pusat. Protes seringkali tidak didengar.
“Makanya pada sisi kebijakan, pemerintah kabupaten ini sudah mulai berpihak. Tinggal kita kawal, kita dampingi,” ucapnya.
Ia pun berjanji membantu soal proses pencabutan izin di Wawonii dan kriminalisasi warga.
Sementara Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan proyek-proyek berlabel mitigasi krisis iklim itu itu sangat mempengaruhi masyarakat. Mereka punya nilai-nilai sendiri, khususnya terhadap tanah, dan sangat tergantung pada alam.
Ketika mereka justru tersingkir maka hak mereka telah dikesampingkan. Makanya Komnas HAM juga melakukan pemantauan.
"Nah, tapi yang jadi catatan kami, tentu ini juga harus sejalan dengan Hak Asasi Manusia seperti itu,” ucapnya.
SHARE
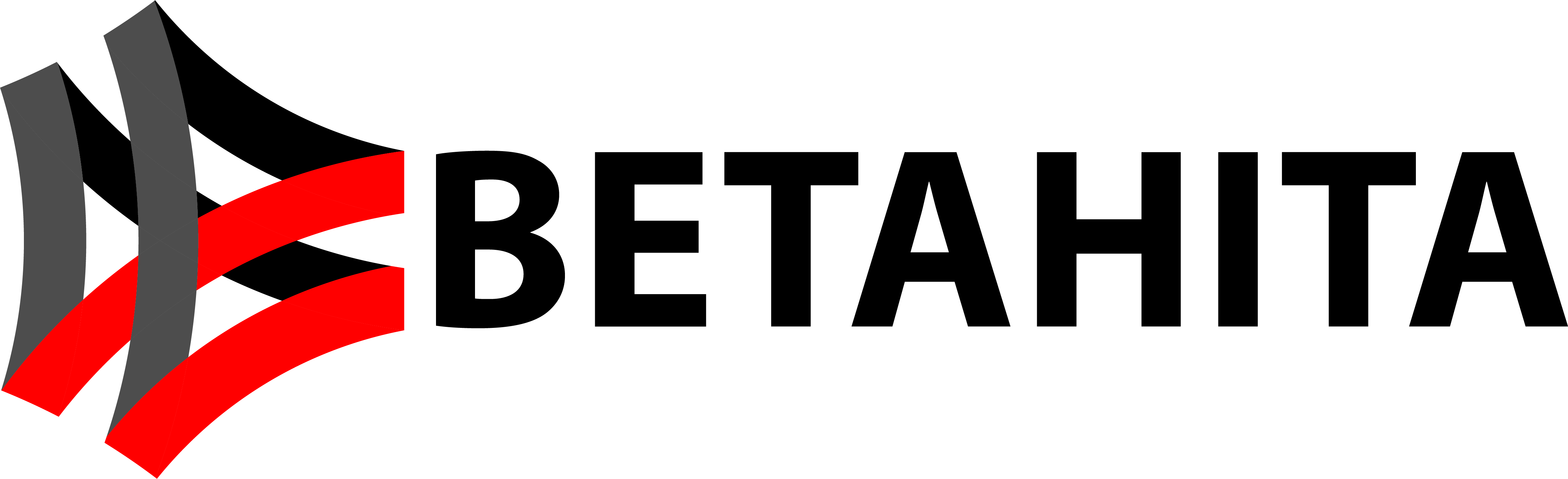


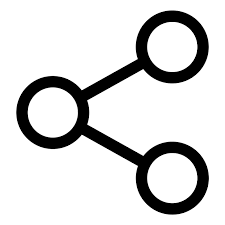 Share
Share

