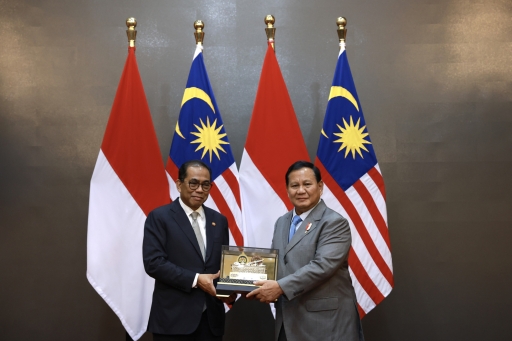Indonesia Disebut akan Terus Bergantung pada Bahan Bakar Fosil
Penulis : Gilang Helindro
Energi
Selasa, 11 Juni 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Laporan Global Energy Monitor (GEM) mengungkapkan, ekspansi pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas ekspor-impor gas alam cair (LNG) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan menyebabkan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya tidak stabil. Tak hanya itu, langkah ini juga akan menurunkan investasi energi terbarukan di Asia Tenggara.
Warda Ajaz, Project Manager for Asia Gas Tracker GEM mengatakan, mengacu laporan bertajuk Southeast Asia’s Energy Crossroads: The Cost of Gas Expansion versus The Promise of Renewable tersebut, Indonesia berpotensi menjadi negara importir gas sepenuhnya pada 2040. "Indonesia memang memiliki cadangan gas terbesar ketiga di Asia Pasifik, tetapi produksi gasnya terus turun setelah mencapai puncak pada 2010," ujarnya.
Di sisi lain, pemanfaatan gas domestik kini telah melampaui volume ekspor, dan diperkirakan terus naik menjadi 24 persen dalam bauran energi 2050. “Pada saat itu, impor gas Indonesia diproyeksikan menyentuh lebih dari 30 persen dari total kebutuhan seiring dengan rencana ekspansi infrastruktur gas di Indonesia,” kata Warda, dikutip Senin, 10 Juni 2024.
Data GEM menunjukkan, ada 14 gigawatt (GW) proyek pembangkit listrik tenaga gas dalam pengembangan, dengan hampir 5 GW di antaranya memasuki masa konstruksi. Sebagai negara pengekspor LNG terbesar keenam dunia, Indonesia punya fasilitas ekspor LNG berkapasitas 23 juta ton/tahun (million tonnes per annum/mtpa) yang telah beroperasi dan 12 mtpa dalam pengembangan. Indonesia tercatat memiliki fasilitas impor LNG terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 15 mtpa sudah beroperasi dan 2,3 mtpa dalam pengembangan.

Indonesia bukan satu-satunya di Asia Tenggara yang ekspansi infrastruktur gas besar-besaran. GEM mencatat, terdapat total 100 GW pembangkit listrik tenaga gas, 47 mtpa fasilitas impor LNG, dan 16,7 mtpa fasilitas ekspor LNG, yang sedang dikembangkan di Asia Tenggara. Biaya Pembangunan seluruh fasilitas tersebut mencapai US$220 miliar. Indonesia bersama Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand berada di garis terdepan dalam ekspansi ini.
Padahal, mengacu laporan GEM, Asia Tenggara bisa memenuhi pertumbuhan energinya dengan energi terbarukan, yang harganya semakin kompetitif dan emisinya lebih rendah dari gas. Rata-rata biaya pembangkitan listrik (levelized cost of electricity/LCOE) energi surya di Asia Tenggara saat ini berkisar US$ 70-95/megawatt hour (MWh) dan energi angin US$ 105-135/MWh, dibandingkan gas US$ 80-125/MWh. Biaya energi surya dan angin diperkirakan turun signifikan jika Asia Tenggara sukses mengembangkan energi surya dan angin secara masif.
Rencana pengembangan energi surya dan angin di Asia Tenggara, jika berhasil dibangun, akan menghasilkan listrik 450 terawatt hour (TWh) per tahun, setara 2/3 proyeksi permintaan listrik di wilayah ini pada 2030. Selain itu, GEM menegaskan, pengembangan energi terbarukan domestik yang dilengkapi baterai penyimpanan energi menawarkan kesempatan bagi negara Asia Tenggara untuk terbebas dari tekanan pergerakan harga gas di pasar global.
“Permintaan energi terus meningkat di seluruh wilayah Asia Tenggara seiring dengan bertambahnya ekonomi, tetapi meningkatkan produksi gas bukan solusi jangka panjang. Memenuhi kebutuhan dengan energi terbarukan yang lebih hemat biaya, akan mengamankan wilayah Asia Tenggara dari harga gas yang tidak stabil, dan merupakan jalur yang lebih hijau ke depannya,” kata Warda Ajaz, Project Manager for Asia Gas Tracker.
Laporan GEM menyatakan, lembaga keuangan internasional berperan penting dalam rencana pengembangan fasilitas gas di Asia Tenggara. Berbagai mekanisme pendanaan yang ada membuat Asia Tenggara sulit beralih dari energi energi fosil. Sebagai contoh, Just Energy Transition Partnership (JETP) bertujuan menyediakan bantuan pendanaan bagi negara berkembang yang masih bergantung pada batubara untuk beralih ke energi bersih.
Namun, Indonesia dan Vietnam yang telah meluncurkan inisiatif JETP, justru akan menggunakan pendanaan ini untuk mengembangkan infrastruktur gas. Proposal JETP Indonesia memasukkan rencana konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel ke gas, meski ada isu emisi gas. Sementara Vietnam berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas untuk menggantikan PLTU batubara.
Mekanisme JETP, dengan tujuan membangun transisi energi yang adil, memberi kewenangan pada masing-masing negara untuk menetapkan strategi menuju sistem energi yang lebih bersih. Namun, tanpa pembatas yang jelas, mekanisme JETP justru menyediakan insentif buruk yang mengunci negara-negara Asia Tenggara dalam ketergantungan pada gas. Padahal, pendanaan internasional seharusnya bisa mendukung pengembangan proyek surya dan angin, serta meningkatkan stabilitas jaringan listrik regional.
Selain itu, melalui pendanaan bilateral, Jepang merupakan salah satu yang terbesar mendanai proyek gas di Asia Tenggara. Empat bank Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group, dan Mitsubishi UFJ memberikan total pembiayaan US$9,7 miliar dalam dekade terakhir. Langkah ini disinyalir sebagai upaya mengamankan ketahanan energi Jepang dan membantu perusahaan utilitas Jepang menjual beban kelebihan kontrak kargo LNG seiring turunnya permintaan dalam negerinya.
SHARE



 Share
Share