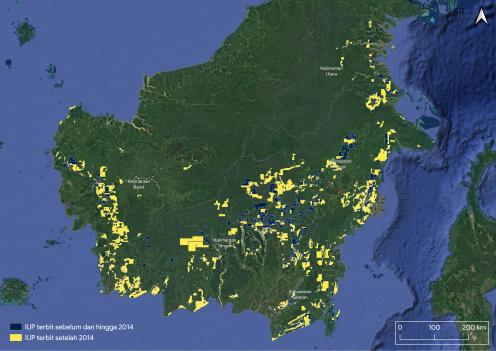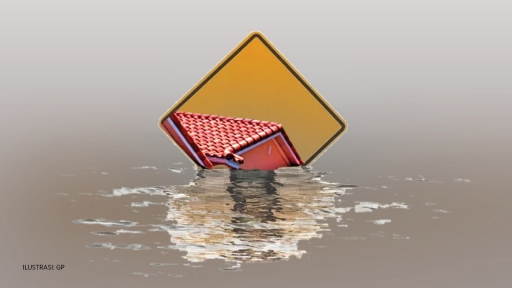SANDHYAKALANING JAWADWIPA
Penulis : Yosep Suprayogi, PEMIMPIN REDAKSI BETAHITA.ID
EDITORIAL
Senin, 16 Februari 2026
Editor : Raden Ariyo Wicaksono
PADA mulanya adalah nama. Dan pada nama itu ada sebuah takdir.
Dua ribu tahun lampau, ketika kartografer Aleksandria, Claudius Ptolemaeus, menarik garis di atas papirus untuk memetakan dunia timur yang samar, ia berhenti di sebuah koordinat. Di sana, di sabuk khatulistiwa itu, ia menuliskan satu kata: Iabadiou.
Ptolemaeus menuliskan nama itu tak sekadar untuk menandai lokasi. Nama itu adalah kesannya atas sumber daya di atasnya, setelah membaca log pelayaran para pelaut yang mengunjungi pulau itu. Iabadiou—atau Jawadwipa dalam lidah Sanskerta—berarti "Pulau Jelai", pulau padi-padian.
Nama itu menegaskan bahwa pulau ini, dengan deretan gunung berapi yang rutin memuntahkan kesuburan dari perut bumi, telah dipahat oleh alam sebagai sebuah lumbung. Peradaban di atasnya—mulai dari Sailendra hingga Mataram, dari Majapahit hingga Republik ini—berdiri di atas satu mandat: menumbuhkan pangan.

Selama berabad-abad, kita hidup dalam kenyamanan mitos itu. Kita percaya bahwa tanah ini begitu gemah ripah, hingga tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Kolamnya dari susu. Kita percaya pada “Sawah Abadi " sebagai keniscayaan sejarah.
Sampai kemudian, data datang mengetuk pintu seperti seorang juru sita.
Hari ini, jika kita mengaudit lanskap Jawa, kita terpaksa harus bertanya: Masihkah nama "Jawadwipa" itu relevan, ataukah ia telah menjadi sebuah sarkasme?
Mari kita tinggalkan sejenak baris-baris puisi dan beralih ke angka-angka akuntansi. Mari kita bicara tentang air—darah yang menghidupi nama Yava (padi) itu.
Di meja kerja para perencana negara di Jakarta, tersimpan sebuah dokumen neraca yang mengerikan. Sebuah angka-angka yang jika dibacakan, terdengar seperti vonis kematian bagi ambisi swasembada.
Fakta itu berbunyi demikian:
Setiap tahun, di pulau yang padat ini, total tagihan kebutuhan air—untuk mengairi sawah-sawah yang kita banggakan, untuk membasuh tubuh 150 juta manusia, dan untuk mendinginkan mesin-mesin industri—tercatat sekitar 164,1 miliar meter kubik.
Itu ada di kolom permintaan. Lalu, apa yang tersedia di brankas alam?
Data yang sama menunjukkan, pasokan air riil yang bisa diandalkan—air yang tidak hilang menguap atau langsung mengalir menjadi banjir karena hutan di hulu telah gundul—hanyalah sekitar 101,4 miliar meter kubik.
Sebuah operasi aritmatika yang brutal. Ada kekurangan sebesar 62,7 miliar meter kubik setiap tahun. Padahal angka ini sudah diset optimistis, mencakup semua air yang tersedia, baik yang bersih maupun beracun. Jika air tak layak dikeluarkan, ketakberimbangannya lebih besar lagi. Mengutip pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup, defisit air di Pulau Jawa pada 2024 sebesar 118 Miliar meter kubik.
Jadi, ini bukan sekadar defisit, tapi kebangkrutan hidrologis.
Pulau ini sedang mengalami insolvensi. Kita memaksa hidup dengan gaya boros air di atas neraca yang tekor. Lalu, dari mana kita menutupi kekurangan 62 miliar kubik itu?
Kita—sebenarnya mereka, pabrik dan industri—mencurinya dari masa depan. Air tanah dalam (deep groundwater) di akuifer-akuifer purba dikuras, tak peduli bahwa butuh ribuan tahun untuk terisi kembali. Hasilnya, kita membiarkan tanah di Pantura amblas ditelan laut karena rongga buminya kosong-kerontang.
Sementara waduk-waduk raksasa—Jatiluhur di Jawa Barat, Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Sutami di Jawa Timur—yang seharusnya menjadi jantung irigasi Jawadwipa, kini mendangkal oleh lumpur erosi, kehilangan jutaan kubik kapasitasnya setiap tahun. Mereka ini adalah monumen dari kegagalan kita merawat bentang alam di hulu.
Maka, ketika pada hari ini pemerintah menetapkan peraturan tentang "Lahan Sawah Dilindungi", kita patut bertanya: Di atas tanah mana padi itu akan tumbuh? Dengan air apa ia akan dibesarkan?
Menggunakan undang-undang dan Perpres untuk mempertahankan ilusi sebagai lumbung pangan di atas pulau yang bangkrut secara air adalah sebuah fiksi hukum dan administrasi yang berbahaya.
Jawadwipa sedang perlahan dihapus dari masa depan. Suku kata Yava (padi) sedang lepas, huruf demi huruf, digerogoti oleh kebutuhan, tapi juga keserakahan, dan salah urus.
Dan kita, anak-anak sejarah yang lalai, mungkin suatu hari nanti hanya akan mewariskan separuh nama yang tersisa kepada masa depan:
Dvipa.
Hanya sebuah pulau. Sebuah pulau yang pernah subur, dahulu kala.
SHARE



 Share
Share