PLTU Pacitan dan Wajah Ketimpangan Baru di Teluk Kondang
Penulis : Muhammad Gufron, YOGYAKARTA
OPINI
Rabu, 19 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Teluk Kondang, Kecamatan Sudimoro, Pacitan bukan sekadar infrastruktur energi. PLTU telah menciptakan krisis dalam bentuk ketergantungan ekonomi, pencemaran lingkungan, hingga peminggiran kelompok masyarakat lokal. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) belum mampu menjawab berbagai tantangan konflik lingkungan, perampasan ruang hidup, dan penurunan taraf hidup masyarakat warga.
Sejak 2024, PLTU Pacitan menerapkan sistem co-firing, teknologi pencampuran batubara dengan biomassa berupa serbuk kayu (abuk). Upaya ini diklaim sebagai langkah menuju energi bersih. Namun, lonjakan permintaan biomassa justru memunculkan pola eksploitasi baru.
Di jalur menuju Pantai Ndaki, berdiri fasilitas penggilingan kayu berukuran besar yang memproduksi abuk dalam skala industri. Hampir semua jenis kayu diterima, kecuali kelapa dan sawit. Pelbagai jenis kayu, seperti jati, mahoni hingga sengon, digiling menjadi serbuk dan dikirim ke PLTU setiap hari. Satu truk pengangkut bisa membawa 8 hingga 12 ton abuk dengan harga sekitar Rp250 ribu per ton.
Kondisi itu mengubah arah ekonomi lokal. Para petani jamur dan pembudidaya cacing telah kehilangan bahan baku yang dulu mudah didapat gratis dari penggergajian. Dampaknya, kini marak penebangan pohon di kawasan hutan karst. Meningkatkan risiko erosi dan kekeringan.

Hilangnya tutupan vegetasi di karst juga mengancam ketersediaan air tanah bagi pertanian dan permukiman di sekitarnya. Alhasil, program co-firing justru berpotensi menimbulkan deforestasi terselubung di wilayah yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan resapan air.
Selain tekanan terhadap hutan, masyarakat juga menghadapi persoalan limbah. Abu sisa pembakaran batubara (bottom ash) menumpuk di area terbuka sisi timur PLTU. Saat kemarau, limbah abu halus akan melayang ke permukiman warga, Kecamatan Sukorejo dan Sudimoro. Lambat laun, partikel mikron fly ash berisiko mengganggu kesehatan pernapasan.
Sebagian limbah dimanfaatkan untuk urugan jalan desa atau bahan bangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemanfaatan itu hanya mengurangi volume limbah, sementara penyebaran logam berat seperti arsenik, timbal, dan merkuri dapat mengontaminasi tanah dan air tanah.
Seperti yang terjadi pada air Sungai Bawur, saluran pembuangan air panas dari sistem pendingin turbin PLTU. Suhu air di sungai ini kerap meningkat saat pembangkit beroperasi penuh. Memusnahkan biota kecil seperti ikan impun dan udang kecung yang dahulu melimpah. Warga juga mencatat kasus wisatawan yang kulitnya melepuh setelah mencuci kaki di air sungai tersebut.
Fenomena ini menunjukkan potensi pelanggaran Peraturan Menteri LHK No. P.15/2019 yang mewajibkan PLTU dengan sistem pendingin terbuka untuk memantau suhu, pH, dan kandungan logam berat secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada publik. Hingga kini, kewajiban tersebut belum dijalankan secara transparan.
Tidak hanya kerusakan ekosistem di darat. Laut di sekitar Teluk Kondang kini kehilangan banyak sumber daya hayati. Sejak area itu dikeruk untuk pembangunan, ikan hampir tidak ditemukan lagi di perairan sekitar PLTU. Aktivitas tongkang pengangkut batubara menambah beban lingkungan.
Kapal yang terguling atau muatannya tumpah saat badai, menyebabkan batu bara dan oli yang tumpah mencemari laut. Para nelayan juga mencatat peningkatan frekuensi petir di sekitar wilayah teluk, diduga akibat sistem penangkal petir PLTU yang mengalihkan sambaran ke laut. Situasi ini membuat banyak nelayan enggan melaut saat cuaca buruk.
Kawasan konservasi penyu yang dulu menjadi kebanggaan Pacitan kini ikut terdampak. Sejak 2019, populasinya menurun drastis, bahkan seekor penyu pernah tersedot ke saluran air PLTU dan mati terluka parah.
Sementara di Pantai Kili-Kili, bantuan perusahaan lebih berfokus pada infrastruktur wisata seperti gapura, patung penyu, dan spot foto. Padahal, yang dibutuhkan adalah pemulihan ekosistem dan pembatasan cahaya di malam hari agar penyu dapat bertelur dengan aman. Lampu tambak udang dan sorot cahaya dari PLTU membuat pantai semakin terang, menjauhkan penyu dari garis pasir.
Di bukit Cagak Telu, perusahaan membangun Cafe Energi, program CSR yang dikelola pemerintah desa setempat. Dari kafe kecil itu, pengunjung dapat melihat cerobong PLTU menjulang di balik Teluk Kondang. Panorama yang tampak “modern” itu justru menutupi realitas lain. Panorama cerobong asap yang ad di PLTU mengalihkan perhatian dari permasalahan deforestasi. Hutan di belakangnya kian gundul akibat penebangan untuk pasokan biomassa.
Di waktu bersamaan, beredar rencana pembangunan pabrik semen di kawasan yang sama, memanfaatkan kedekatan dengan sumber batu gamping dan limbah batubara dari PLTU. Industri demi industri bertumbuh di atas tanah yang sama, sementara ruang hidup warga terus menyempit.
PLTU Pacitan juga menimbulkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial muncul di isu ketenagakerjaan. PLTU Pacitan menempatkan sekitar 300 pekerja lokal di posisi seperti petugas kebersihan dan sopir. Jabatan teknis dan manajerial diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi Ketenagakerjaan semakin rumit ketika muncul praktik-praktik percaloan untuk kebutuhan tenaga kerja di PLTU. Praktik percaloan muncul untuk posisi-posisi seperti satpam atau cleaning service. Praktik calo untuk ketenagakerjaan di PLTU menunjukkan bahwa praktik-praktik kolusi dan nepotisme masih banyak terjadi di PLTU Pacitan.
Sebagian besar pekerjaan bersifat sementara atau borongan. Petugas kebersihan dikontrak dua bulan dan dibayar kolektif per proyek. Sementara teknisi lokal hanya dipanggil dua kali setahun untuk perawatan turbin. Pola kerja tak tetap ini membuat warga tetap rentan tanpa jaminan pendapatan berkelanjutan.
Di sekitar lokasi PLTU, wajah demografi desa pun berubah. Banyak rumah di Sudimoro dan Sukoharjo kini ditempati pendatang yang bekerja di sektor energi. Petani yang kehilangan lahan beralih menjadi buruh atau pekerja kasar. Muncul tambak-tambak udang baru yang membuang limbah langsung ke laut melalui pipa besar di Pantai Ndaki, membuat pasir di sekitarnya menghitam.
Ketimpangan ditimbulkan oleh PLTU Pacitan bukan sekadar siapa mendapat pekerjaan dan siapa yang tidak. Program CSR yang digadang-gadang sebagai bentuk kepedulian sosial pun lebih sering hadir dalam wujud yang “diciptakan” untuk kebutuhan warga sekitar. Padahal pada praktiknya CSR yang dilakukan oleh PLTU adalah pelumas kapitalisme. Sebut saja seperti perbaikan jalan menggunakan cor, gapura, kafe wisata, patung penyu, hingga CSR dalam bentuk yang paling banal, yaitu limbah FABA untuk kebutuhan bangunan warga. Sebut saja seperti jalan cor digunakan untuk mempercepat distribusi kebutuhan PLTU, meskipun di sisi lain warga juga memanfatkan jalan tersebut.
Kafe wisata yang dibangun PLTU juga bagian dari perluasan usaha yang dilakukan PLTU. Perusahaan mencoba untuk melakukan akumulasi di sektor Food and Beverage (FnB) melalui industri pariwisata. PLTU memperkenalkan limbah Fly ash, Bottom ash (FABA) sebagai material bangunan. PLTU mengkampanyekan pemanfaatan FABA untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai bentuk komitmen untuk pengelolan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan. Padahal, FABA yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan merupakan FABA yang telah dikelola, sementara PLTU Pacitan memberikan FABA tersebut dalam bentuk mentah hasil pembakaran batu bara. FABA sebagai program CSR tentu saja semakin menguntungkan PLTU. Apabila pemanfaatan dilakukan secara optimal, PLTU tidak perlu mengeluarkan cost-produksi untuk pengelolaan limbah. Di sisi lain, masyarakat menjadi kelompok yang harus menerima dampak kesehatan karena pemanfaatan FABA yang belum diolah.
Alih-alih bertanggungjawab atas kerusakan ekosistem lingkungan dan peminggiran masyarakat lokal, kemunculan PLTU justru memunculkn krisis-krisis baru seperti pencemaran, penurunan pendapatan masyarakat, penciptaan ketergantungan ekonomi. Kelompok-kelompok masyarakat lokal dipaksa untuk terus beradaptasi dengan PLTU. Mereka dipaksa untuk mentoleransi degradasi lingkungan, penghilangan ruang hidup, pemaksaan perubahan pola produksi dan penciptaan ketergantungan ekonomi. Alih-alih menjawab persoalan mendasar seperti pencemaran udara, rusaknya sumber air, serta hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani. Masyarakat pesisir tentu paling terdampak dan selalu di posisi paling rapuh. Tanpa akses terhadap pengambilan keputusan, pekerjaan layak, maupun lingkungan hidup yang sehat.
Artikel ini merupakan hasil fellowship yang diadakan oleh WALHI Yogyakarta tahun 2025 tentang transisi energi.
SHARE
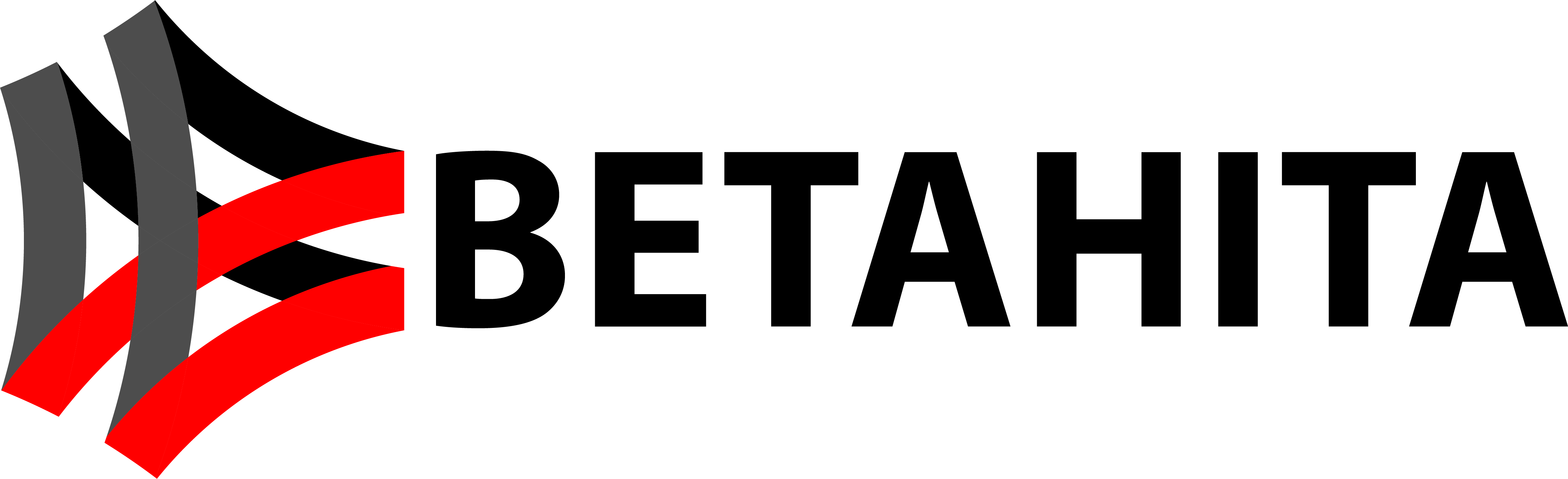


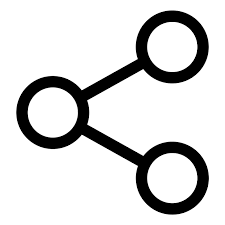 Share
Share

