COP30: Pemerintah Diminta Kembali ke Rakyat, Kembali ke Akar
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Iklim
Selasa, 18 November 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Tuntutan “Kembali ke Rakyat-Kembali ke Akar” disuarakan di sela gelaran Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) agar pertemuan iklim dunia dapat berjalan di jalur yang sebenarnya, yaitu keadilan iklim.
Menurut Walhi, seluruh pengurus negara di dunia harus kembali pada rakyat, yakni merekognisi hak, peran, pengetahuan, dan praktik tradisional rakyat dalam menyusun aksi adaptasi dan mitigasi iklim. Mengubah sistem ekonomi politik tidak lagi mengejar pertumbuhan, dan tidak mengkonsentrasikan kekuatan hanya di tangan korporasi dan negara adalah keniscayaan untuk menjawab akar persoalan krisis iklim.
Walhi menyebutkan, setidaknya sejak satu dekade lalu, pada COP21 di Paris, pasca8-komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5°C disepakati, hingga kini dunia tidak bergerak maju. Bahkan banyak data yang menyebutkan bahwa sepanjang 2024 menjadi tahun terpanas. World Meteorological Organization (WMO) menyatakan rata-rata suhu global sekitar 1,55°C ± 0,13°C di atas periode 1850-1900.
Fakta ini adalah konsekuensi jika pertemuan COP hanya sebagai ruang untuk menyediakan solusi dari mereka yang selama ini menyebabkannya. Bahkan menurut analisis terbaru Koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO), lebih dari 1600 pelobi bahan bakar fosil diberikan akses ke perundingan iklim COP30 di Belem, termasuk Indonesia.

Sebanyak 46 pelobi bahan bakar fosil dalam delegasinya dan mengintervensi negosiasi pasal 6.4 terkait pasar karbon untuk melonggarkan aturan pasar karbon, termasuk standar integritas lingkungan yang lebih lemah dan perlindungan longgar terhadap proyek offset berbasis alam berisiko tinggi, yang dinilai bertentangan dengan sains dan target 1,5°C.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menganggap fakta di atas semakin membuktikan bahwa negara telah “diambil alih” oleh korporasi dengan memberikan akses istimewa kepada mereka untuk mempengaruhi kebijakan iklim, dengan melonggarkan aturan pasar karbon, agar para pebisnis fosil dapat dengan mudah meng-offset emisi, sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnis karbon.
“Praktik corporate capture yang dilakukan Indonesia semakin membuktikan bahwa tidak ada agenda keselamatan rakyat dan lingkungan dalam misi delegasi Indonesia. Kita tidak mau terlambat menyelamatkan kehidupan kita, itulah kenapa kami menyuarakan Kembali ke Rakyat-Kembali ke Akar, sebagai call to action dalam COP30 ini, baik dalam aksi global di Belem, maupun aksi serentak di Indonesia,” kata Uli dalam keterangan tertulis, Minggu (16/11/2025).
Desakan ini juga disampaikan oleh Walhi bersama dengan jaringan dan komunitas di delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Sulawesi Tengah.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT, Yuven Stefanus Nonga, menyampaikan suara dari pulau kecil sebagai wilayah yang paling rentan berhadapan dengan krisis iklim. Ia bilang, perempuan, anak, masyarakat adat, nelayan, petani yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah entitas yang paling rentan saat berhadapan dengan krisis iklim.
Yuven menuturkan, masyarakat tersebut hidup di garis depan krisis iklim di tanah yang retak, laut yang naik, dan gunung yang dieksploitasi atas nama transisi hijau. Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah menjadikan kerentanan wilayah dan situasi masyarakat di tapak, di seluruh daerah menjadi basis utama dalam menyusun kebijakan iklim berikut dengan agenda aksi dan adaptasinya.
“Kami percaya jawaban itu bisa ditemukan jika negara kembali ke rakyat,” katanya.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugrah, juga menyampaikan bahwa komitmen iklim Indonesia saat ini masih jauh dari memutus ketergantungan pada energi kotor. Menurutnya, kebijakan dikeluarkan justru membuka jalan bagi ekspansi industri ekstraktif yang merugikan rakyat dan lingkungan di Jambi.
Transisi energi berkeadilan, lanjut Oscar, hanya dapat diwujudkan apabila negara kembali ke rakyat dan mendengarkan suara rakyat, khususnya perempuan. Karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian iklim dan ancaman dari proyek-proyek energi selama ini.
“COP30 bukan hanya ruang untuk diplomasi, tetapi harus menjadi titik balik untuk memastikan dan mengawal terwujudnya keadilan ekologis, keadilan gender dan masa depan ruang hidup rakyat Jambi,” ujarnya.
Pada aksi COP30 di Sulawesi Tengah (Sulteng), Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng, Sunardi Katili, menganggap bahwa penyelenggaraan COP30 di Belem, Brazil hanyalah pertemuan palsu. Ia berpendapat, negara-negara utara hanya terus memindahkan krisis ke negara selatan. Ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk kolonialisasi iklim.
Sunardi mengatakan, perdagangan karbon bukan jalan keluar menyelesaikan krisis iklim yang sedang terjadi, justru sebaliknya mengamankan industri korporasi besar di Indonesia. Mestinya pengurangan emisi dilakukan langsung dari industrinya, seperti industri pengolahan nikel yang masih gunakan PLTU captive batu bara di Morowali dan Morowali Utara Sulteng.
“Ada IMIP, IHIP, SEI, Transon Group, Wangxiang bahkan IGIP kawasan industri baru yang akan dibangun di Morowali meski belakangan akan gunakan energi gas, PLTG sebagai pembangkit listrik dalam kawasan. Sudah seharusnya menghentikan aktivitas industri ekstraktif dan berhenti membangun yang baru,” kata Sunardi.
Desakan untuk kembali ke rakyat dalam menjawab akar persoalan krisis iklim harusnya di rekognisi oleh pengurus negara. Sebab, menurut Walhi, umat manusia tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk terus membiarkan para penghasil emisi karbon untuk terus menyusun solusi-solusi palsu iklim. Mengingat suhu global yang naik 1,5°C bisa menimbulkan ancaman kekeringan bagi 951 juta orang (IPCC).
IPCC memperkirakan, jika suhu naik 2°C bencana kekeringan bisa melanda 1,15 miliar orang, kemudian mengancam 1,28 miliar orang jika kenaikannya sampai 3°C. Selain bencana kekeringan, IPCC menilai kenaikan suhu global di atas 1,5°C bisa memicu degradasi lingkungan, menurunkan produksi pertanian, hingga melahirkan masalah sosial-ekonomi.
SHARE
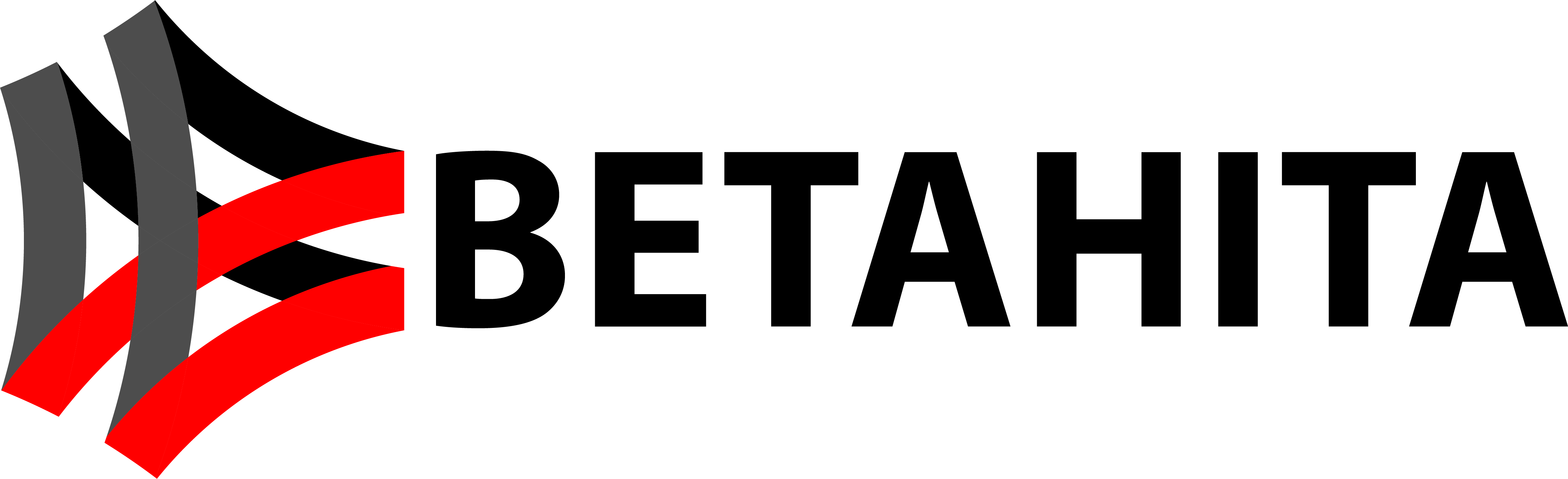


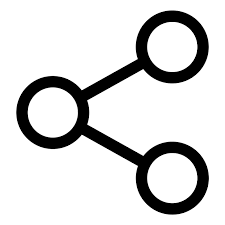 Share
Share

