Dari Hutan Kongo di Barat, Amazon di Timur, Bersepakat di Papua
Penulis : Muhammad Ikbal, PAPUA
Masyarakat Adat
Rabu, 01 Oktober 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Para pemuda adat dari empat kawasan hutan tropis terbesar di dunia mendeklarasikan sikap bersama dalam menjaga hutan dan hak masyarakat adat di Kampung Sira, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Deklarasi ini lahir dalam kegiatan Forest Defender Camp (FDC) 2025, yang digelar Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Perkumpulan Bentang Nusantara Papua dari 23 hingga 26 September 2025.
Para pemuda yang berasal dari Cekungan Kongo, Amazon, Borneo, dan Tanah Papua menyatakan diri sebagai pembawa pengetahuan leluhur sekaligus pelindung sistem kehidupan. Mereka menegaskan hutan bukan hanya milik masyarakat adat, tetapi juga penopang bagi seluruh umat manusia.
"Kami adalah pemuda adat, pembawa pengetahuan leluhur, dan pelindung sistem kehidupan yang menopang bukan hanya masyarakat kami, tetapi seluruh planet," bunyi pernyataan bersama.
Dalam deklarasi tersebut, mereka menyoroti ancaman serius yang dihadapi masyarakat adat, mulai dari ekspansi pertambangan dan perkebunan, pembalakan skala industri, kekerasan militer, hingga kriminalisasi aktivis lingkungan.

Selain itu, lemahnya regulasi dan kegagalan negara meratifikasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) serta ILO No. 169 dinilai memperburuk situasi.
Para pemuda adat juga mendesak pengakuan resmi terhadap batas wilayah adat, penghentian operasi militer, serta partisipasi penuh perempuan dan pemuda adat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menuntut adanya mekanisme pendanaan langsung bagi organisasi adat, serta integrasi pengetahuan tradisional ke dalam kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati.
Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menilai generasi muda Papua memiliki peran penting menghadang laju proyek strategis nasional (PSN) yang terus masuk ke Tanah Papua. Menurut dia, masa depan Papua ditentukan oleh pilihan pemuda adat Papua.
“Ini soal masa depan mereka. Apakah menerima masa depan yang ditentukan sepenuhnya oleh PSN atau memperjuangkan alternatif yang lebih baik,” kata Leonard dalam Forest Defender Camp (FDC) 2025 di Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Jumat pekan lalu.
 Forest Defender Camp 2025 di Sorong Selatan. (Foto: Muhammad Ikbal)
Forest Defender Camp 2025 di Sorong Selatan. (Foto: Muhammad Ikbal)
FDC kali ini diikuti ratusan pemuda dari tujuh wilayah adat Papua. Isu utama yang dibicarakan adalah dampak proyek ekstraktif, seperti tambang, perkebunan, dan infrastruktur berskala besar, yang dinilai semakin mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Leonard mengatakan pemerintah pusat masih memandang Papua semata sebagai lumbung sumber daya alam. “Narasi besar pembangunan dari Jakarta cenderung eksploitatif dan ekstraktif,” ujarnya. Ia menambahkan, PSN diberi keleluasaan besar hingga bisa menerabas aturan lingkungan. “Mereka seolah diberi cek kosong. Amdal bisa dipinggirkan, konsultasi masyarakat hanya formalitas. Itu bahaya sekali,” katanya.
Namun Leonard membantah anggapan bahwa penolakan PSN berarti anti pembangunan. Ia menyebut Greenpeace dan pemuda Papua sama-sama menginginkan kesejahteraan. “Yang dipersoalkan adalah model pembangunan. Industri ekstraktif hanya akan memperdalam peminggiran masyarakat dan memperparah kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Leonard, Greenpeace hanya memberi ruang konsolidasi. Arah gerakan ada di tangan pemuda Papua. “Kekuatan ada pada seberapa solid kalian membangun jaringan kampanye dan advokasi,” katanya.
Leonard menyatakan harapan harus tetap ada, meski persoalan berat. "Tapi harus disertai komitmen kuat untuk belajar, berkonsolidasi, dan mengorganisir. Karena yang kita hadapi ini bukan perkara biasa,” ujarnya.
Hidup yang Kian Menjauh dari Laut
Raja Ampat, Papua Barat Daya. Laut pernah jadi halaman rumah bagi warga Pulau Kawe. Dari situlah mereka menggantungkan hidup: memancing banyak jenis ikan, mencari udang dan teripang, hingga mengolah ikan asin untuk dijual ke Sorong.
“Dulu kami bisa melaut sehari dan kembali dengan puluhan kilogram ikan,” kata Jefri Dimalouw, 30 tahun, pemuda asal Kampung Salio, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat.
Namun, suasana itu berubah sejak tambang nikel beroperasi di Pulau Kawe. Menurut Jefri, aktivitas tambang membuat air laut di sekitar pulau keruh, terutama setelah hujan. Ikan pun kian sulit ditemukan. “Sekarang, kalau mau dapat ikan, kami harus melaut lebih jauh. Bahan bakar minyak yang dulu cukup lima liter, kini bisa habis sampai 15 liter sekali melaut,” ujarnya.
Jefri masih ingat masa sebelum perusahaan tambang turun ke pulau sekitar 2008. Kala itu, laut Raja Ampat menjadi lumbung pangan. Perahu-perahu nelayan singgah ke kampung Salio dan Selpele untuk menjual hasil laut, sementara warga pesisir hidup tanpa kekhawatiran akan kelaparan. “Masyarakat tidak kaya, tapi cukup. Laut memberi makan semua orang,” kenangnya.
Masuknya dua perusahaan tambang nikel ke Pulau Kawe memicu konflik batas wilayah konsesi. Perselisihan itu sempat berujung ke meja hijau di Pengadilan Jayapura hingga Mahkamah Agung. Salah satu perusahaan kemudian hengkang, tapi yang lain kembali beroperasi pada 2021. Sejak itulah, Jefri merasakan degradasi ekosistem semakin nyata.
Bagi generasi muda, kata Jefri, ancaman tambang bukan semata kerusakan alam. Lebih jauh, ia khawatir tambang yang berizin 25 tahun itu akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekaligus warisan untuk generasi mendatang. “Baru tiga tahun beroperasi saja sudah terasa dampaknya. Bagaimana 20 tahun lagi? Anak cucu kami mungkin tidak lagi bisa hidup dari laut dan hutan,” ucapnya dengan nada khawatir.
Perusahaan, menurut dia, mencoba meredam keresahan warga dengan kompensasi uang tunai. Satu keluarga bisa menerima Rp6-15 juta sebulan tanpa bekerja. Namun, Jefri melihat hal itu sebagai jebakan. “Kalau hanya uang yang kita lihat, kita bisa terlena. Tapi dampak buruknya jauh lebih besar. Uang bisa habis, tapi hutan dan laut yang rusak tidak bisa kembali,” ujarnya.
Paulina Awom, 24 tahun, pemuda adat asal Kampung Kabare, Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sempat ditangkap polisi ketika melakukan aksi penolakan tambang nikel. Aksi tersebut berlangsung dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, Selasa, 3 Juni lalu.
Paulina bersama tiga pemuda Papua lain dan sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan spanduk penolakan tambang nikel yang merusak ekosistem laut dan hutan di Papua. Mereka ditangkap aparat kepolisian, namun dibebaskan beberapa jam kemudian.
Paulina berkata, sebelum tambang beroperasi, masyarakat Raja Ampat hidup dari laut dan kebun, termasuk membuat kopra dari kelapa. Namun, setelah tambang masuk, banyak tanaman digusur, karang laut rusak, dan populasi ikan menurun. “Banyak karang rusak, ikan mulai hilang, bahkan ada yang punah,” kata Paulina.
Ia menyebut respons masyarakat terhadap tambang terbelah. Sebagian menolak, tetapi lebih banyak menerima dengan alasan tawaran pekerjaan dari perusahaan. “Tapi dampaknya kami yang tanggung. Hutan hilang, laut rusak,” ujarnya.
Paulina juga mengungkapkan tantangan anak muda di Raja Ampat yang jarang terlibat dalam menyuarakan penolakan tambang. “Kebanyakan sibuk kuliah atau sekolah, jadi tidak terlalu mau terlibat,” katanya.
Melalui FDC 2025, Paulina dan Jefri berharap dapat mengajak lebih banyak anak muda dan warga di kampungnya untuk berdiskusi tentang dampak tambang. Ia mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin tambang dibuat secara tertulis agar tidak membingungkan masyarakat.
Masalah Lingkungan di Kongo Dinilai Serupa Papua
Persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat adat di Republik Demokratik Kongo dinilai serupa dengan situasi masyarakat adat di Papua. Kedua kawasan hutan tropis terbesar dunia itu sama-sama berhadapan dengan ancaman penebangan liar, ekspansi industri ekstraktif, diskriminasi, dan marginalisasi.
“Kami menghadapi penebangan ilegal oleh perusahaan internasional asal Tiongkok, diskriminasi, marginalisasi, penangkapan sewenang-wenang, dan perampasan tanah. Hal ini sama seperti yang dialami masyarakat adat di Papua,” kata Gylain Mbale Mola, Masyarakat Adat Kongo.
Gylain berkata pula, praktik perampasan lahan dan lemahnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat memperparah kerentanan komunitas lokal di Kongo. Ia menyebut, banyak kesepakatan perlindungan hak masyarakat adat yang diabaikan oleh pemerintah maupun korporasi.
Untuk menjaga hutan, komunitas adat di Kongo berupaya mengembangkan pertanian kecil, peternakan, dan pola produksi pangan yang berkelanjutan. “Kami berusaha melindungi hutan dengan cara yang bertanggung jawab agar tidak sepenuhnya bergantung pada hutan,” ujarnya.
Mbale Mola menekankan pentingnya solidaritas antar-pemuda adat dari empat kawasan hutan tropis dunia: Cekungan Kongo, Amazon, Borneo, dan Papua. Menurut dia, suara kolektif anak muda menjadi kunci untuk menekan negara dan korporasi agar menghentikan praktik perusakan hutan.
“Hutan adalah identitas dan masa depan kita. Apa yang kami alami di Kongo juga dialami di Papua. Karena itu kita harus bersatu, memperjuangkan hutan untuk kehidupan, bukan untuk dihancurkan,” tuturnya.

SHARE
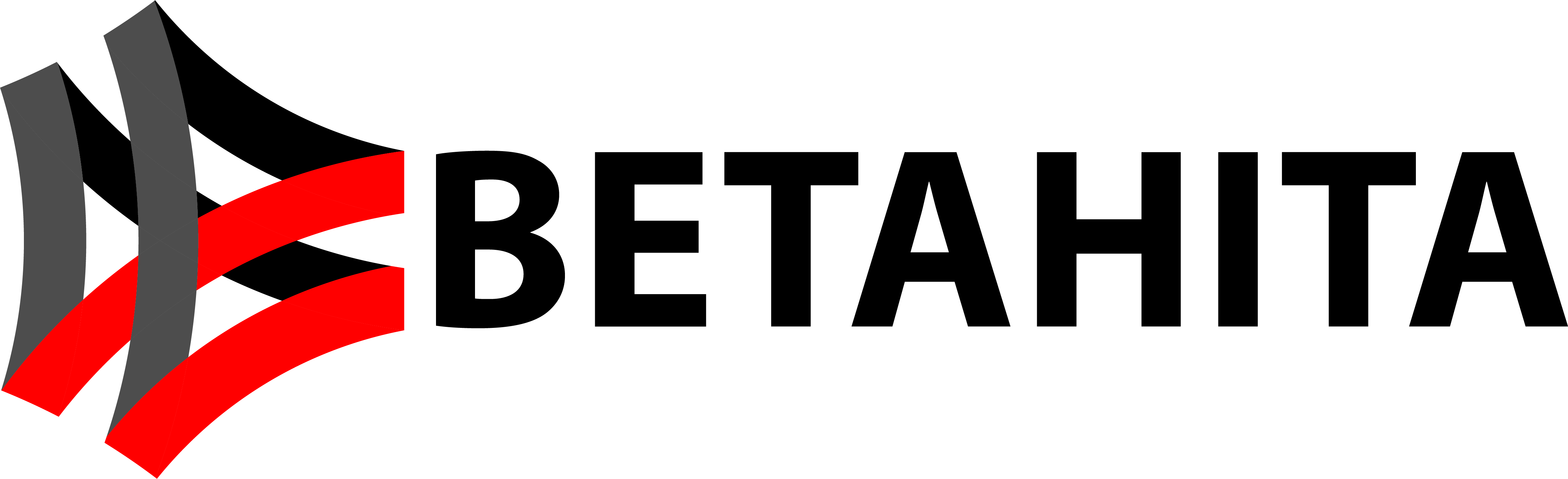


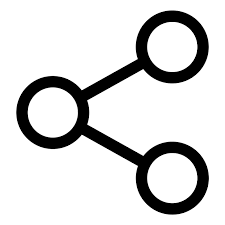 Share
Share

