Keanekaragaman Hayati: Adu Balap Ilmuwan x Deforestasi
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
SOROT
Senin, 27 Mei 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Ancaman malaria tak membuat Iyan Robiansyah kapok untuk kembali menjelajahi Pulau Mursala. Sekitar dua pekan lalu, ia menginjakkan kakinya lagi ke pulau tersebut, untuk yang ketiga kalinya, demi melihat lagi jenis-jenis tumbuhan langka terancam punah, khususnya Dipterocarpus cinereus, yang sudah ia tandai pada kunjungan sebelumnya.
Tapi betapa kaget Iyan saat mendapati tiga pohon dewasa bernama lokal lagan bras atau pelahlar mursala itu sudah tak lagi berdiri tegak, hanya tersisa tunggul dan potongan batang saja. "Sudah ditebang. Sepertinya illegal logging ya. Saya juga kaget. Padahal 2022 lalu sudah kami ploting secara permanen untuk di-monitoring," kata Iyan, Sabtu (25/5/2024).
Iyan mengatakan, jenis Dipterocarpus cinereus ini sangat langka dan endemis. Di dunia, jumlahnya hanya puluhan saja--30 individu dewasa menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), dan hanya ditemukan di Pulau Mursala. Pulau seluas sekitar 8 ribu hektare ini terletak di sebelah barat Pulau Sumatra, secara adminstratif masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Iyan mengatakan, tutupan hutan di Pulau Mursala terbilang lebat, citra satelit pun memperlihatkan begitu. Tapi bila dilihat langsung di lokasi, cukup mudah didapati beberapa titik terjadinya penebangan liar, terutama terhadap Dipterocarpus cinereus. "Jenis ini kayunya memang cukup bagus dan memang jadi incaran para penebang liar. Selain tiga pohon dewasa itu, pohon-pohon kecil juga ditebang untuk buat jalan angkut kayu," ungkap Iyan.

Iyan merupakan Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga tergabung dalam Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI). Iyan melakukan Ekspedisi Pulau Mursala selama 2 pekan, bersama 9 mahasiswa Univeritas Sumatera Utara (USU), dan dua peneliti dari Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI) lainnya. "Kebetulan hari ini hari terakhir ekspedisi. Alhamdulillah lancar," kata Iyan.
Meski sedih tiga pohon pelahlar mursala ditebang, tapi Iyan merasa ekspedisi kali ini tidaklah sia-sia. Karena ia dan tim ekspedisi juga masih berhasil melihat jenis-jenis tumbuhan langka lainnya di pulau tersebut, yakni jenis Drybalanops aromatica (barus), Vatica venulosa subsp. simalurensis (resak minyak), dan Hopea bancana (merawan).
Sayangnya, penebangan liar bukan satu-satunya cerita buruk. Sebab, Iyan dan tim ekspedisi juga menemukan adanya pembukaan perkebunan sawit baru di pulau kecil itu. Ekspansi perkebunan ini, menurut Iyan, menjadi ancaman lain bagi pohon-pohon langka, dan tentu menambah tekanan terhadap habitatnya. Karena pembangunan perkebunan sawit akan melibatkan pembersihan lahan, bila di hutan alam akan mengakibatkan deforestasi.
Iyan mengatakan, hidup Dipterocarpus cinereus sudah cukup sulit, sehingga tumbuhan ini tak butuh gangguan lain terhadap habitatnya. Iyan bilang, spesies penyandang status critically endangered atau kritis di IUCN Red List ini, sulit beregenerasi.
Dari puluhan bibit yang tumbuh alami, imbuh Iyan, hanya satu atau dua individu saja yang pada akhirnya berhasil tumbuh sampai dewasa. "Karena perebutan nutrisi dari tanah dan sinar matahari. Untuk dewasa dan menghasilkan anakan dia butuh puluhan bahkan ratusan tahun," kata Iyan.
 Salah satu peneliti FPLI, Mokhamad Nur Zaman, duduk di dekat satu dari tiga pohon dewasa Dipterocarpus cinereus yang ditebang di Pulau Mursala. Foto: Iyan Robiansyah.
Salah satu peneliti FPLI, Mokhamad Nur Zaman, duduk di dekat satu dari tiga pohon dewasa Dipterocarpus cinereus yang ditebang di Pulau Mursala. Foto: Iyan Robiansyah.
Hal yang juga mengkhawatirkan, Iyan melanjutkan, Pulau Mursala ternyata juga masuk dalam wilayah kerja PT Multi Sibolga Timber, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam--dulu disebut hak pengelolaan hutan (HPH), sejak 2007. Untungnya saat ini perusahaan tersebut belum beroperasi di pulau tersebut.
Iyan mengaku sudah bertemu dengan pihak perusahaan tersebut dan menyampaikan keberadaan sejumlah spesies tumbuhan langka dan terancam di Mursala. "Dan ternyata mereka tidak tahu kalau ada tumbuhan langka di Pulau Mursala. Tapi sudah kita kasih masukan ke mereka," ujar Iyan.
Walau begitu, keberadaan Dipterocarpus cinereus dan jenis-jenis dilindungi lainnya di Mursala masih "telanjang", kapan saja mereka bisa hilang. Sebab, jenis-jenis itu tidak termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi.
Ya, pada Juni 2018 lalu Dipterocarpus cinereus dan 9 jenis tumbuhan langka dan terancam punah lainnya pernah menyandang status dilindungi. Sayangnya, status dilindungi itu hanya bertahan 6 bulan saja, sebelum dicabut lagi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal yang disesalkan banyak peneliti tumbuhan. "Tapi BRIN sudah mengusulkan agar tumbuhan-tumbuhan itu dilindungi lagi," ucap Iyan.
Kekayaan biodiversitas Indonesia
Meski nasibnya di ujung tanduk, tapi Dipterocarpus cinereus adalah salah satu spesies yang membuat Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati terkaya di dunia, konon nomor 2 setelah Brazil. Saking kayanya, jumlah spesies satwa dan tumbuhan di Indonesia sulit dipastikan angka akhirnya, sebab para peneliti masih melaporkan penemuan jenis (spesies) baru dari berbagai daerah.
Pada 2017, Indonesia memiliki 31.750 jenis tumbuhan yang telah ditemukan (Retnowati dan Rugayah, 2019) dan 25.000 di antaranya merupakan tumbuhan berbunga (LIPI, 2021). Menurut LIPI–kini disebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat, namun baru sekitar 7.000 spesies yang digunakan sebagai bahan baku obat.
Sedangkan faunanya, LIPI menyebut Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amphibi. Indonesia juga memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi (Lasabuda, 2013).
Di antara fauna darat (terestrial) maupun perairan itu sebagian merupakan fauna endemik, hanya ada di Indonesia. Menurut LIPI (2021), terdapat 97 spesies ikan terumbu karang dan 1.400 spesies ikan air tawar yang hanya terdapat di Indonesia.
Sumber lain, dari 15.960 spesies yang masuk dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List–belum termasuk subspesies dan varietas yang jumlahnya 156 individu, spesies yang berstatus endemik jumlahnya sebanyak 4.202. Spesies endemik ini terdiri dari 3 kingdom, yakni 1 fungi, 1.298 plantae, dan 2.903 animalia.
Tahun lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga melaporkan 49 penemuan taksa baru, yang mana 37 persen taksa baru tersebut paling banyak ditemukan di Sulawesi. Terdiri dari fauna yang berjumlah 1 marga, 38 spesies, dan 2 subspesies. Sisanya adalah flora 7 spesies, dan mikroorganisme 1 spesies.
 Kolase temuan taksa baru di 2023. Foto: BRIN
Kolase temuan taksa baru di 2023. Foto: BRIN
Beberapa spesies taksa baru untuk kelompok fauna merupakan fauna endemik Indonesia, yang berasal dari Maluku, Kepulauan Natuna, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. 31 persen kelompok fauna endemik ini adalah spesies baru kepiting, cacing laut, udang, ikan, keong, cecak, dan hewan pengerat.
Beberapa fauna endemik spesies baru seperti Pectinaria nusalautensis yang ditemukan di Pulau Nusalaut Maluku, merupakan spesies cacing polychaeta laut ketujuh yang diidentifikasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, enam dari delapan taksa baru krustasea yang ditemukan, satu marga dan empat spesies kepiting merupakan endemik dari Pulau Natuna dan Pulau Siantan, sedangkan satu spesies udang endemik Caridina clandestine berasal dari Sulawesi Tengah.
Untuk fauna endemik lainnya, yaitu cecak Cyrtodactylus gonjong ditemukan di Sumatera Barat, ikan Oryzias loxolepis ditemukan di Sulawesi Selatan, keong Palaina motiensis ditemukan di Maluku Utara, dan empat hewan pengerat yaitu Rattus feileri, Rattus taliabuensis, Rattus halmaheraensis, dan Rattus obiensis ditemukan di Maluku.
Menurut BRIN, penemuan spesies baru ini memiliki arti penting bagi studi taksonomi dan biosistematika. Lebih jauh, penemuan ini menjadi awal dari penelitian biodiversitas (keanekaragaman hayati) selanjutnya, seperti konservasi hingga bioprospeksi.
Meski begitu kaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penurunan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tinggi. Menurut Sutarno dan Setyawan (2015) dari 20 negara yang jenis-jenis (spesies) alamiahnya terancam, Indonesia menduduki posisi kelima dan menurut Nasional Geografi Indonesia (2019), Indonesia menduduki urutan keenam sebagai negara dengan kepunahan biodiversitas terbanyak.
IUCN sendiri mencatat 7 spesies di Indonesia sudah menyandang status extinct atau punah (5 punah dan 2 punah di alam) yakni Mangifera casturi (kasturi kalimantan), Macrobrachium leptodactylus (udang air tawar), Coryphomys buehleri (tikus raksasa), Chitala lopis (belida), Etlingera heyneana (honje), Amomum sumatranum (jahe hutan sumatra), dan Urolophus javanicus (pari jawa).
Kemudian yang lainnya, 408 spesies berstatus critically endangered (kritis terancam punah), 856 spesies endangered (terancam punah), 1.234 spesies vulnerable (rentan), 1.011 spesies near threatened (hampir terancam) dan 10.345 spesies least concern (risiko rendah).
Pemerintah memang sudah memberikan label "dilindungi" kepada 904 jenis tumbuhan dan satwa, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.106 Tahun 2018. Sayangnya status dilindungi ini tidak lantas membuat habitat jenis-jenis itu juga ikut dilindungi.
Dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati
Padahal beberapa peneliti dan akademisi sepakat, deforestasi merupakan salah satu musuh terbesar bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. I Putu Gede Ardhana dalam jurnalnya menyimpulkan, menipisnya hutan alam berpotensi mengakibatkan terjadinya kepunahan pada tingkat keanekaragaman spesies, genetik dan ekosistem. Peneliti lainnya, Nanang Jainuddin, mengatakan deforestasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati.
Yang pertama, kehilangan habitat dan kepunahan spesies, yang mana dua hal tersebut saling terkait. Deforestasi, atau penghilangan hutan secara besar-besaran, merusak ekosistem yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Kehilangan habitat ini mengakibatkan spesies-spesies tersebut kehilangan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak. Seiring berkurangnya luas habitat alami, spesies-spesies ini terancam kepunahan karena mereka tidak lagi memiliki kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup.
Duenas dkk. (2021) menyatakan, kehilangan habitat akibat deforestasi secara signifikan mengancam spesies-spesies yang mengandalkan hutan sebagai tempat tinggal. Tanpa habitat yang sesuai, spesies-spesies ini menghadapi risiko penurunan populasi dan bahkan kepunahan.
Dalam kasus Indonesia, deforestasi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies endemik, yang hanya ditemukan di hutan-hutan Indonesia. Deforestasi yang berlanjut, akan mengakibatkan kepunahan spesies. Kepunahan ini memiliki dampak jangka panjang pada keragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan.
Dampak yang kedua, menurut Nanang, adalah fragmentasi habitat dan perubahan ekosistem. Fragmentasi habitat merupakan fenomena di mana hutan atau ekosistem alami terpotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat aktivitas deforestasi atau perkembangan manusia. Fenomena ini mengakibatkan terbentuknya "pulau-pulau" habitat yang terisolasi, yang dapat memiliki dampak negatif pada populasi spesies dan interaksi ekologis.
Meijaard et al. (2005) mengamati bahwa di pulau-pulau Indonesia, fragmentasi habitat yang terjadi akibat deforestasi dan penggunaan lahan dapat memisahkan populasi spesies-spesies penting seperti harimau, gajah, dan badak. Fragmentasi ini menghambat pergerakan dan migrasi alami spesies-spesies tersebut antara area yang terisolasi.
Akibatnya, spesies-spesies ini mengalami kesulitan dalam mencari makanan, berkembang biak, dan menjaga keragaman genetik yang diperlukan untuk kelangsungan populasi yang sehat. Fragmentasi habitat juga dapat mengubah dinamika ekosistem secara keseluruhan.
Kehadiran koridor hutan yang tersisa antara bagian-bagian yang terfragmentasi dapat membantu dalam pergerakan spesies dan menjaga interaksi antarspesies yang penting. Namun, jika koridor ini terganggu atau hilang, ekosistem dapat berubah drastis. Interaksi predator-mangsa, penyerbukan oleh hewan, dan perpindahan nutrisi menjadi terganggu, berpotensi mengakibatkan penurunan keragaman spesies dan perubahan dalam struktur ekosistem.
Penelitian Meijaard et al. (2005) menggarisbawahi bahwa fragmentasi habitat akibat deforestasi di Indonesia tidak hanya memengaruhi spesies-spesies tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan alami ekosistem yang penting bagi kelangsungan hayati dan fungsi ekosistem secara keseluruhan.
Yang ketiga dampak migrasi dan kelangsungan hidup. Nanang menganggap dampak satu ini juga cukup mengkhawatirkan. Deforestasi, katanya, mengganggu pola migrasi dan perilaku berkembang biak beberapa spesies, berdampak langsung pada populasi dan kelangsungan hidup mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al. (2017) menyoroti bagaimana deforestasi dapat mengubah pola migrasi burung-burung di Kalimantan. Deforestasi mengurangi ketersediaan habitat alami yang biasanya mereka gunakan selama perjalanan migrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, akibat deforestasi, burung-burung tersebut menghadapi kesulitan dalam menemukan tempat berlindung dan sumber makanan selama perjalanan mereka.
Akibatnya, pola migrasi yang biasanya teratur menjadi terganggu, dan beberapa spesies burung mengalami penurunan populasi. Beberapa spesies bahkan mungkin menghentikan migrasinya sama sekali, karena tidak dapat menemukan kondisi yang sesuai untuk bertahan hidup selama perjalanan.
Dampak ini sangat penting untuk dipahami, karena migrasi burung memiliki peran penting dalam ekologi dan distribusi tanaman. Penyerbukan oleh burung-burung migratori, misalnya, dapat mempengaruhi reproduksi tanaman dan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, deforestasi yang mengganggu migrasi burung-burung ini memiliki efek berantai yang dapat merusak keseimbangan ekosistem.
"Gangguan pada migrasi dan perilaku spesies, seperti burung, dapat mengganggu pola migrasi dan berpotensi merugikan ekosistem," kata Nanang dalam sebuah jurnal berjudul Dampak Deforestasi Terhadap Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, yang terbit 2 Agustus 2023.
 Dari ketinggian tampak kondisi Pulau Wawonii akibat pertambangan nikel. Foto: Jatam Nasional.
Dari ketinggian tampak kondisi Pulau Wawonii akibat pertambangan nikel. Foto: Jatam Nasional.
Tak hanya itu, deforestasi juga dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya alam tumbuhan obat, beserta pengetahuan tradisional masyarakat akan kegunaannya. Di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, misalnya, para peneliti mencatat terdapat 73 jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bahan obat tradisional dan perawatan pasca-persalinan. Tiga jenis di antara tetumbuhan obat tersebut termasuk dalam daftar tumbuhan langka di Indonesia, yaitu Alstonia scholaris (L.) R.Br., Arcangelisia flava (L.) Merrill, dan Fibraurea tinctoria Loureiro.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)--kini disebut BRIN--mencatat kurang lebih 1.000 jenis tumbuhan ada di Pulau Wawonii. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga di Pulau Wawonii memanfaatkan sekitar 200 jenis tumbuhan sebagai bahan pangan, papan, obat dan kosmetika, hingga anyaman dan sumber energi.
Pakar Taksonomi Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Rugayah, mengatakan, kekayaan ragam jenis tanaman di Wawonii merupakan aset luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia, dan harus dijaga agar generasi mendatang dapat melihat dan mengenalnya. Wawonii, menurutnya, merupakan contoh pulau kecil di Indonesia yang harus dijaga keberlangsungan ekosistemnya.
"Saya yakin masyarakat akan sejahtera dengan kepedulian atas lingkungan yang menciptakan inovasi-inovasi tinggi. Wawonii bisa menjadi pulau terdepan, mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain," ujar Rugayah, yang pernah melakukan penelitian di Pulau Wawonii, pada 2003-2005 silam, dalam sebuah diskusi yang digelar, Selasa (22/8/2023).
Tak hanya tumbuhan obat, pulau kecil Wawonii juga memiliki keragaman jenis anggrek yang tinggi. Diah Sulistiarini, mencatat ada sebanyak 91 jenis anggrek dari Pulau Wawonii. Berdasarkan jumlah jenisnya, paling banyak dijumpai di Lampeapi ada 43 jenis (19 jenis di antaranya hanya dijumpai di Lampeapi), Wawolaa 29 jenis (9 jenis hanya di Wawolaa) Langsilowo 20 jenis (11 jenis hanya di Langsilowo), Dompo-Dompo 18 jenis (5 jenis hanya di Dompo-Dompo), Wongkolo 14 jenis (1 jenis hanya di Wongkolo) dan Waworete 13 jenis (7 jenis hanya di Waworete).
Tapi kekayaan hayati pulau seluas 650 km persegi itu tengah terancam. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada dua izin tambang PT Gema Kreasi Perdana (Nikel)--anak usaha Harita Group–yang berada di kecamatan yang berbeda, pertama terdapat di Kecamatan Wawonii Barat dan Tengah dengan luas izin 958 hektare dan Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 850,9 hektare sehingga jika dijumlahkan menjadi 1.808,9 hektare. Keberadaan tambang nikel ini dikhawatirkan merusak biodiversitas di pulau itu.
Bergeser ke Maluku Utara, Pulau Obi sebagai bagian dari kawasan biogeografi Wallacea memiliki keragaman flora dan fauna yang menarik dengan tingkat endemisitas yang tinggi, khususnya kelompok avivauna (burung). Tapi aktivitas pembukaan lahan di pulau tersebut juga menyebabkan keterisolasian dan fragmentasi habitat yang beragam dan kepunahan spesies serta tekanan pertumbuhan populasi.
Peneliti menjumpai beberapa jenis fauna di areal pertambangan PT Trimegah Bangun Persada (PT TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (PT GPS)--anak usaha Harita Group, seperti kuskus obi (Phalanger rothschildi), nuri kalung ungu (Eos squamata obiensis), serta soa-soa (Hydrosaurus amboinensis) dan kupu-kupu (Jamides celeno).
Terbaru, puluhan ribu hektare habitat orangutan kalimantan (Pongo pygmaues wurmbii) di Kalimantan Barat dibabat untuk pembangunan kebun kayu oleh PT Mayawana Persada. Akibatnya, selain berpotensi mengakibatkan orangutan menjadi hidup secara terisolasi, juga membuat primata tersebut menjadi gelandangan karena kehilangan rumahnya.

Luas deforestasi di Indonesia
Celakanya, deforestasi di Indonesia tidak berkesudahan, tiap tahun selalu terjadi. Menurut analisis Auriga Nusantara, dalam rentang waktu 2001 hingga 2022, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 10.201.927 hektare. Paling luas terjadi di Kalimantan sebesar 4.303.116 hektare, dan Sumatra sebesar 4.037.216 hektare. Sedangkan deforestasi di Sulawesi dan Papua, luasnya masing-masing 909.516 hektare dan 657.943 hektare.
Bila dilihat lebih dalam, deforestasi 2001-2022 tersebut lebih dari setengahnya, atau sekitar 5.815.544 hektare, terjadi di habitat sejumlah satwa endemik dan dilindungi, khususnya orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), orangutan sumatra (Pongo abelii), orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis), bekantan (Nasalis larvatus), badak kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis harrisoni), badak sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus), harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae), babirusa (Babyrousa), anoa (Bubalus sp.), julang sumba (Rhyticeros everetti), komodo (Varanus komodoensis) dan macan tutul jawa (Panthera pardus melas).
Sedangkan hutan alam tersisa di habitat satwa-satwa tersebut, pada 2022, luasnya sekitar 35.986.104 hektare. Di regional Kalimantan luasnya 16.107.256 hektare, Sulawesi 9.856.170 hektare, Sumatra 8.722.188 hektare, Maluku 731.304 hektare, Jawa 536.661 hektare, dan Nusa Tenggara 32.515 hektare.
Sementara pada 2023, Auriga melaporkan deforestasi di Indonesia mencapai angka 257.384 hektare. "Angka tersebut lebih besar dari angka tahun 2022 yang sebesar 230.760 hektare," kata Dedi P. Sukmara, Direktur Informasi dan Data, Yayasan Auriga Nusantara, Selasa (21/5/2024).
Angka deforestasi di Indonesia 2023 versi Auriga Nusantara itu, bila dilihat lebih jauh, 47,3 persen atau sekitar 121.728 hektare terjadi di areal yang sudah dibebani perizinan usaha, terutama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pertambangan, dan perkebunan sawit.
Dilihat dari status fungsi kawasannya, deforestasi paling banyak justru terjadi di kawasan hutan negara yang pengelolaannya di bawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yakni seluas sekitar 188.394 hektare. Sisanya sebesar 68.839 hektare terjadi di areal penggunaan lain (APL), dan 151 hektare di tubuh air.
Yang menarik sekaligus ironis, dari angka deforestasi Indonesia 2023 yang dirilis Auriga Nusantara pada Maret itu, deforestasi pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi luasnya cukup besar, mencapai 12.631 hektare. Dedi berpendapat deforestasi di kawasan hutan konservasi ini adalah hal yang ironis. “Karena, kawasan yang seharusnya terproteksi dan bebas dari gangguan, malah mengalami deforestasi dengan luasan yang lumayan besar," ujarnya.
Pendapat Dedi itu bukan tanpa alasan. Karena, menurut pengertiannya berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Deforestasi 12.631 hektare itu, secara rinci, terjadi di suaka margasatwa seluas 4.342 hektare, di taman nasional seluas 4.267 hektare, di cagar alam sebesar 3.035 hektare, di taman hutan raya 331 hektare, di taman wisata alam 173 hektare, di taman buru 29 hektare, dan di kawasan konservasi lainnya seluas 435 hektare.
SHARE
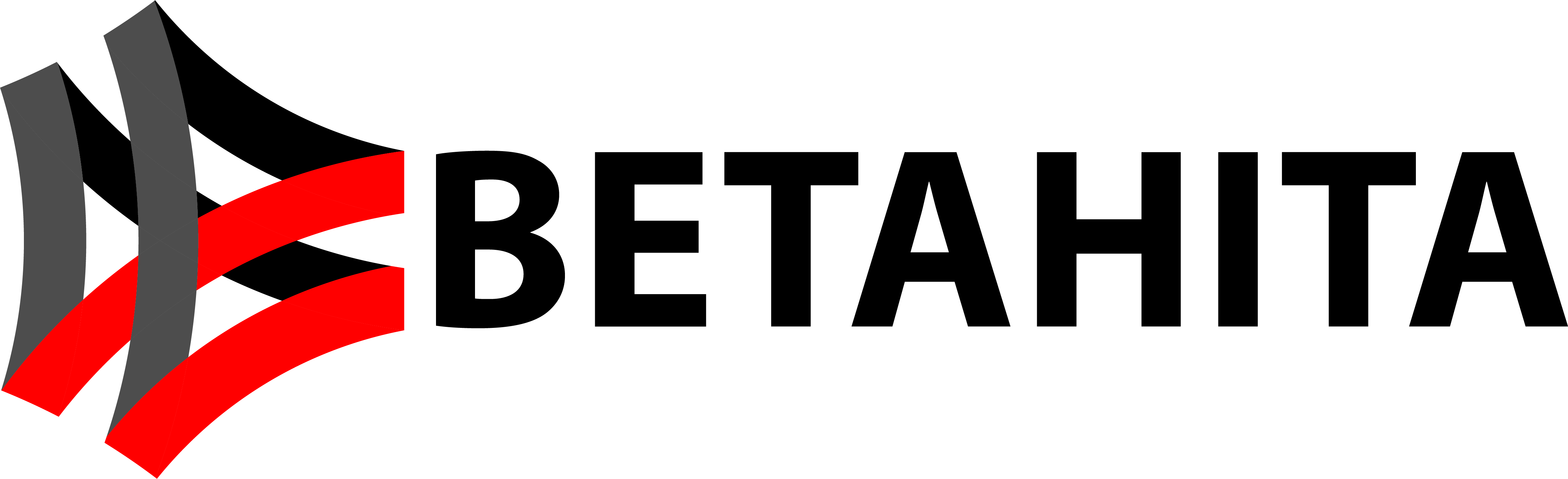


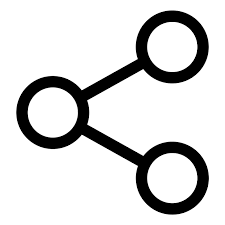 Share
Share

